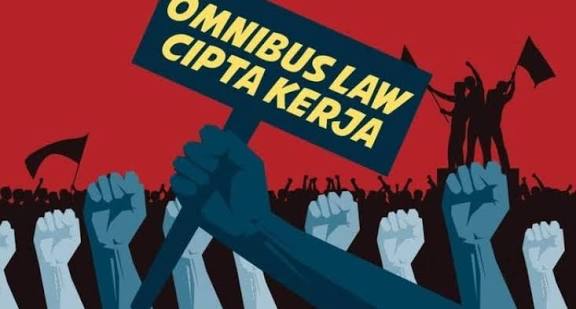Penulis : Mirza Budiansyah, Mahasiswa MIH FH UNJA
Tuntutan adaptasi di era globalisasi menempatkan negara pada posisi yang sulit. Hukum dituntut bergerak cepat, memangkas birokrasi, dan membuka karpet merah bagi investor dalam menempatkan investasi. Di Indonesia, respons terhadap tuntutan ini diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau yang dikenal sebagai Omnibus Law.
Dalam kacamata Sosiologi Hukum, lahirnya undang-undang ambisius ini adalah upaya nyata dari konsep Law as a tool of social engineering (Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial), sebagaimana digaungkan oleh Roscoe Pound. Hukum, melalui proses legislasi, diharapkan menjadi instrumen untuk menertibkan, memajukan, dan merekayasa struktur sosial demi kesejahteraan bersama. Namun, pertanyaan krusial yang harus diajukan adalah: Apakah Undang Undang Cipta Kerja telah berhasil menjalankan peran rekayasa sosial ini, atau justru menciptakan kesenjangan antara teks hukum dan realitas sosial di masyarakat?
Cacat Formil dan Legitimasi Sosiologis yang Terkoyak
Pandangan Sosiologi Hukum terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berkutat pada kepatuhan prosedural (formil), tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut mendapatkan legitimasi sosial (pengakuan dan penerimaan dari masyarakat).
Proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja telah terbukti cacat secara formil, pasca hak uji materil (judicial review) di Mahkamkah Konsitusi (MK) dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut inkonstitusional bersyarat. Dari perspektif sosiologis, cacat formil ini adalah manifestasi dari kegagalan mengakomodasi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
Sosiologi Peraturan Perundang-undangan mengajarkan bahwa hukum yang baik harus mencerminkan “kenyataan hukum” dan kebutuhan masyarakat yang diatur. Ketika proses legislasi dilaksanakan secara tergesa-gesa dan dikritik hanya mengakomodasi kepentingan elite tertentu (khususnya investor), maka hukum tersebut kehilangan legitimasi sosiologisnya. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi solusi rekayasa sosial justru berubah menjadi pemicu resistensi berkelanjutan dari serikat pekerja/buruh dan aktivis lingkungan, koalisi masyarakat, sampai akademisi dan pakar, sebagaimana fakta aktual yang terus terjadi saat ini.
Implementasi Hukum dan Kesenjangan Realitas Sosial
Kesenjangan sosiologis semakin terlihat jelas pada substansi Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan yang menjadi episentrum utama konflik.
Pemerintah berargumen bahwa Undang-Undang ini adalah jalan tengah antara tuntutan investasi global dan perlindungan pekerja, dengan tujuan utama membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, fakta aktual di lapangan dan pandangan para sosiolog hukum menunjukkan adanya pemunduran hak-hak normatif pekerja, yang menggeser keseimbangan ke arah yang lebih menguntungkan pemilik modal.
Penguatan Outsourcing: Perluasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan berpotensi menciptakan hubungan kerja yang semakin rentan dan tidak pasti. Pekerja terancam kehilangan kepastian kerja, yang secara sosiologis akan berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga dan melemahkan daya tawar kolektif mereka.
Formulasi Upah Minimum: Pembatasan formulasi upah minimum yang lebih kaku dikhawatirkan menahan laju peningkatan kesejahteraan buruh. Dalam konteks Sosiologi, kebijakan ini berisiko memperparah ketimpangan dan memperkecil ruang gerak kelas menengah, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat dalam era globalisasi.
Pengurangan Hak Pesangon: Reduksi limit uang pesangon merupakan sinyal pelemahan perlindungan sosial bagi pekerja ketika menghadapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Jika tujuan rekayasa sosial adalah menciptakan ketertiban dan kemajuan, maka implementasi Undang-Undang Cipta Kerja justru menimbulkan kekacauan interpretasi, keresahan, dan perlawanan kolektif. Hukum, dalam kasus ini, tidak dilihat sebagai alat integrasi, melainkan sebagai alat dominasi.
Penutup: Kembali ke Filosofi “Hukum untuk Manusia”
Sebagai mahasiswa Magister Hukum, penting bagi kami untuk mengingatkan bahwa hukum harus kembali pada filosofi dasarnya: Hukum untuk Manusia, bukan Hukum untuk Modal semata.
Undang-Undang Cipta Kerja adalah produk hukum yang lahir dari tekanan globalisasi, tetapi ia harus dievaluasi berdasarkan dampak domestiknya. Sebuah hukum yang ideal adalah hukum yang mampu menciptakan keseimbangan (equilibrium) antara tuntutan ekonomi global (investasi) dan perlindungan hak-hak dasar rakyat (keadilan sosial).
Oleh karena itu, proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan membuka ruang partisipasi yang benar-benar bermakna. Legitimasi sosiologis tidak dapat dipaksakan melalui teks dan prosedur, melainkan harus dibangun melalui dialog, akomodasi kepentingan, dan kesadaran bahwa hukum harus memberi manfaat, bukan keresahan, bagi objek yang diaturnya. Kegagalan mencapai keseimbangan ini berarti kegagalan total dalam menjalankan peran mulia hukum sebagai alat rekayasa sosial.